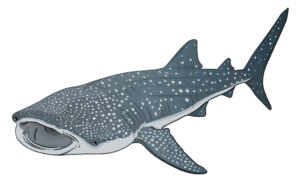Dari lokasi kapal Gurano Bintang melempar sauh, terlihat anak-anak berlarian di tepi laut. Dari kejauhan terlihat bahwa mereka bertelanjang dada. Badannya yang basah mengilap diterpa sinar matahari. Ketika kami menepi dengan sampan, mereka ”bubar jalan”. Mereka beringsut ke pondok mereka masing-masing.
Beberapa anak lain tetap duduk di tangga pondok hanya memakai celana tanpa baju. Mereka tidak menyingkir, tetapi dengan tatapan mata tajam mereka memperhatikan para pendatang.
Ketika makin dekat, kami melihat rambut mereka yang keriting hitam dipuncaki warna cokelat karat. Boleh jadi, mereka terlalu sering berendam di laut. Lalat-lalat juga terlihat mengerubungi kaki-kaki mereka yang penuh luka atau kudis. Ingus hampir merata di pipi karena muka mereka tak pernah bersih dilap. Namun, mereka tetap terlihat ceria.
“Siapa namamu?”
“Melani,” kata seorang bocah berusia sembilan tahun sambil tersenyum malu. Dia lalu bangkit beringsut ke dalam pondok.

Pondok-pondok keluarga mereka berjajar sepanjang pantai membentuk perkampungan baru. Pondok itu serupa gubuk atau rumah panggung dengan berdinding dan beratap anyaman daun nipah. Setidaknya, terdapat 37 pondok keluarga di sana.
Mereka adalah warga dari Nabire dan Teluk Wondama, Papua Barat, yang mencari peruntungan di Pulau Abaruki, Teluk Wondama, sekitar sehari perjalanan naik perahu mesin dari kampung asalnya. Selama Juni-Desember, mereka menetap di pulau itu dengan anak dan istri. Bahkan, ada pula yang mengajak cucu-cucu mereka.
Selama menetap di Pulau Abaruki, puluhan anak yang masuk usia sekolah seharusnya duduk di sekolah taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Namun, mereka terpaksa meninggalkan kelas. Mereka ikut orangtua mereka mencari nafkah. Melani bahkan sudah lupa di mana dia menyimpan seragam sekolah dan alat tulisnya. Padahal, di usia ke-9, dia mengaku belum bisa membaca dan menulis.

Akan tetapi, dia mempunyai pilihan lain selain ikut orangtuanya mencari ikan. Orangtuanya pun tak mungkin meninggalkan anak-anak mereka di kampung halaman tanpa pengawasan. Apalagi, sebagian besar warga ikut berbondong-bondong melaut ke Abaruki.
“Kalau dihitung uang, kitorang bisa peroleh uang Rp 5 juta sebulan,” kata Susance (30), yang juga ibu dari enam anak. Uang didapat meski tidak seorang pun anaknya bersekolah.
Mereka, para nelayan itu, memakai metode nelayan berpindah karena stok ikan di laut dekat kampung halaman mereka tidak sebanyak di Abaruki. Tradisi nelayan berpindah itu sudah berjalan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Mereka ini masuk dalam golongan post-peasant fisher meskipun sudah naik perahu bermesin tempel dengan 2-3 awak kapal. Hasil tangkapan mereka juga belum banyak sehingga hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Siang itu, ketika kami berlabuh adalah hari Minggu. Karena hari itu hari Minggu, para nelayan libur melaut. Walau demikian, karena tidak ada tempat ibadah, warga sembahyang atau berdoa di dalam gubuk. Ada pula nelayan yang mendengarkan khotbah lewat radio. Belasan warga lainnya duduk berjajar di bawah bangku kayu dinaungi rimbun pepohonan.
Minus tempat ibadah, minus sekolah, tentu juga minus fasilitas kesehatan. Ketika menderita sakit, warga biasanya mengandalkan obat tradisional atau obat warung yang dibawa dari kampung.
Tak berdaulat
Kami kemudian melangkahkan kaki menyusuri pesisir. Kami pun melihat asap yang mengepul dari belakang sebuah pondok. Ketika dihampiri, Dessy Wonemseba (22) sedang membalik benda bulat lonjong serupa singkong, yang ketika disentuh terasa kenyal dan menguar aroma amis segar. Itulah teripang yang dikenal sebagai sea cucumber (Holothuroidea). Dessy ternyata sedang mengasapi belasan teripang yang didapat dari laut.
Teripang merupakan salah satu hasil laut yang menjanjikan. Setelah diasapi selama sepekan, hewan lunak itu mengering dan laku hingga Rp 500.000 per kilogram. Teripang digunakan sebagai bahan dasar beragam obat, kosmetik, hingga campuran makanan.
Hasil yang melimpah tentu saja ikan. Sayangnya, warga kesulitan menentukan harga karena dominasi tengkulak (jolor). Harga ikan hanya sekitar Rp 12.000 sampai Rp 15.000 per kilogram. “Para jolor sudah mempermainkan harga dan para nelayan tak bisa apa-apa,” kata Robin Wonemseba (38), nelayan.

Menurut dia, harga itu terlalu murah mengingat harga bensin mencapai Rp 12.000 per liter dan beras sampai Rp 16.000 per kilogram. Dia bahkan menyarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan semacam peraturan dalam penentuan harga ikan sehingga nelayan mempunyai daya tawar.
Ruru (37), tengkulak asal Makassar, yang ”beroperasi” di Pulau Abaruki justru mengaku tidak dapat sembarangan menentukan harga. Menurut Ruru, harga pembeliannya bergantung harga pasar di Nabire. Selain itu, dia juga harus menutupi biaya operasional yang mencapai Rp 5 juta sekali berkeliling mengumpulkan hasil laut dari para nelayan. ”Ini sudah lima hari belum dapat banyak ikan, sementara es batu sudah mulai mencair,” ucapnya.
Nelayan di Pulau Abaruki sesungguhnya dapat meniru langkah para nelayan di Napan Yaur, Kecamatan Teluk Umar, Kabupaten Nabire, yang hidupnya juga bergantung pada laut. Dulu, mereka menjual hasil laut langsung kepada tengkulak dengan harga yang sepenuhnya ditentukan tengkulak. Nelayan bahkan tidak berani menaikkan harga karena hampir semua tengkulak yang datang memberi harga seragam. Misalnya, ikan dengan ukuran kurang dari setelapak tangan hanya dihargai Rp 15.000 per kilogram. Sementara ikan yang lebih besar dihargai Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per kilogram.

Sejak tiga bulan lalu, warga membentuk koperasi yang antara lain berfungsi menampung hasil laut nelayan. Harga ikan yang dijual melalui koperasi menjadi lebih mahal Rp 5.000 sampai Rp 7.000 per kilogram. ”Sekarang kami bisa menabung lebih banyak,” Kata Matius Nuari (29), yang mempunyai simpanan uang Rp 9 juta. Uang itu menurut rencana digunakan untuk resepsi pernikahan dirinya meskipun dia belum menentukan tanggalnya.
Adapun Stefen Abowi (34) dan Matius Wami (53), warga setempat, mengatakan masing-masing mempunyai tabungan Rp 11 juta dan Rp 15 juta. Kata mereka, dengan memperkuat diri dalam wadah koperasi, mereka dapat menyimpan lebih banyak uang hasil melaut.
Para nelayan di Abaruki tadi telah mengorbankan banyak hal. Mereka meninggalkan kampung halaman, menghilangkan kesempatan anak-anaknya untuk bersekolah, tetapi akhirnya hanya memperkaya tengkulak. Bukan akhir perjalanan yang indah bagi mereka.
Matahari pun bersinar terik. Di langit nyaris tak ada awan. Air laut nan jernih berkilauan dan sesekali menunjukkan pasir putih di dasarnya. Melani dan enam temannya berlarian, kemudian menyebur ke laut. Sejuk menghalau terik. Mereka yang tengah bersuka ria tersebut belum sadar bahwa masa depannya belum tentu sejernih air laut itu. (MOHAMMAD HILMI FAIQ)